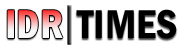Pakewuh yang Membahagiakan

Jakarta –
Saya ini orang yang pakewuhan. Gampang tidak enak hati, mudah merasa sungkan. Saya tahu, Anda pingin bilang, “Halah, nggak nanya, Mas.” Tapi Anda juga pakewuh sama saya, sehingga memilih menahan diri dari ngomong begitu.
Mungkin benar semua ini muncul karena saya orang Jawa, lahir dan dibesarkan di tengah-tengah masyarakat Jawa, sehingga rasa mudah pakewuh itu sudah menubuh dan merasuk ke dalam segenap sistem aliran darah saya. Tetapi saya sendiri melihat teman-teman yang masih pakewuhan tidak melulu orang Jawa, dan di saat yang sama banyak teman saya yang sesama orang Jawa sudah tidak kenal rasa pakewuh itu.
Ini akhirnya menyeret-nyeret kita kepada cerita klise yang sering jadi folklor wajib pada setiap momen per-ghibah-an, yaitu tentang teman atau tetangga yang berutang kepada kita.
Cerita bagian ini agak membosankan, Anda boleh melompatinya. Alkisah, ada seorang tetangga, rumahnya jauh di ujung kampung dan sama sekali tidak pernah berinteraksi dengan saya. Tiba-tiba ia mengetuk pintu rumah saya pada suatu pagi. Setelah sejenak berbasa-basi, dia bilang perlu pinjam uang. Mertuanya meninggal, dan menurut tradisi di kampung mertuanya, mereka harus menyembelih sapi untuk suguhan tamu pelayat yang datang.
Karena istri tetangga saya itu lima bersaudara, pembelian sapi mesti ditanggung berlima. Tapi tetangga saya ti-dak-pu-nya-u-ang (entah, apakah Pak Tetangga tahu bahwa ada potongan video viral pernyataan Pak Prabowo Subianto yang cocok sekali dengan situasi tersebut.) Maka, dia pun meminjam kepada saya.
Memang akhirnya saya meminjami dia uang. Tapi kembali kepada perkara ewuh-pakewuh, setelah dia pergi, saya menggerundel. Dia yang tidak pernah berinteraksi dengan saya, selalu diam saja tiap kali papasan di acara pengajian atau gotong royong kampung, kok tiba-tiba datang dan langsung pinjam uang. Ini benar-benar membuat saya tak habis pikir, kok bisa ya dia tidak pakewuh?
Tetapi, belakangan saya juga tak habis pikir dengan diri saya sendiri. Kenapa sama orang yang tidak pernah beramah tamah dengan saya, saya tetap merasa pakewuh sehingga nggak enak kalau menolak permintaan tolong dia?
Lebih parah lagi, sejak pagi itu, tiap kali kami punya kesempatan berpapasan, entah saat bubaran jumatan atau di acara kondangan manten tetangga sebelum musim korona, kenapa saya yang memilih menghindar? Benar, lagi-lagi pakewuh. Itu yang saya rasakan. Pakewuh kenapa? Itulah misterinya. Mungkin saya pakewuh, nggak enak hati, khawatir kalau-kalau tetangga saya itu merasa pakewuh pas ketemu saya.
Rumit sekali dunia per-pakewuh-an ini, memang.
Pernah dalam kasus lain, istri saya agak mengeluh. “Pakne, kok beberapa teman kita itu kayak nggak pakewuh ya kalau minta tolong ke kita, padahal jenis pertolongan yang mereka minta itu jelas lumayan merepotkan. Tapi giliran kita yang butuh bantuan, meskipun ringan, kita pakewuh mau minta tolong ke mereka….”
Saya terpancing dengan pertanyaan istri saya. Sempat saya mau komplain juga lalu mengutuk-ngutuki hidup yang absurd ini. Namun kemudian saya ingat percakapan saya dengan seorang kawan lama, di sebuah rumah tua di Tebet, Jakarta, juga rentetan peristiwa-peristiwa bermuatan pakewuh yang menyusulnya.
Saya bercerita kepada Yoko, kawan saya itu, bahwa beberapa kali saya mendapat order menulis buku. Itu cuma jenis buku yang sifatnya melayani klien, semacam menulis kisah sukses seseorang, sejarah berdirinya sebuah lembaga, atau peran sosial sebuah industri. Nah, tiap kali mau mengerjakan buku semacam itu, kecemasan selalu datang.
“Misalnya gini, Yok. Kami sudah sepakat nilai honornya segini, pokoknya bagian topik tertentu ditulis semua. Eh, tapi, begitu turun lapangan, wawancara dan sebagainya, ternyata bahannya tidak sebanyak yang aku duga semula. Jadinya ya meskipun tugas selesai, bukunya tipis!”
“Lha trus kenapa? Sudah sesuai kesepakatan, kan?” tanya Yoko.
“Ya sudah. Secara legal sudah beres. Tapi kalau bukunya tipis begitu kan jelek, bikin aku pakewuh.”
“Apa? Pakewuh? Nah, itu yang nggak ada di Jakarta!”
Hahaha. Tawa saya meledak seketika, apalagi kalimat pamungkas itu meluncur dari mulut seseorang yang belasan tahun menjadi penghuni Jakarta. Dan tiba-tiba saya merasa diri ini begitu ndeso, jauh sekali dari spirit kosmopolit, dan menggunakan ukuran-ukuran tak jelas untuk kerja-kerja profesional.
Pakewuh itu wilayah yang tak bisa diukur, sekaligus tak dapat dijadikan sandaran untuk membuat formulasi ukuran-ukuran. Sementara profesionalisme itu mesti terukur, jelas, dan tidak rentan membawa interpretasi macam-macam.
Ketika saya masuk ke dalam dunia yang semestinya profesional, ternyata hati saya tidak kunjung bisa lepas dari dimensi tak jelas dan tidak profesional, yaitu rasa ewuh-pakewuh. Bisakah Anda membayangkan, di sebuah surat perjanjian kerja sama ada satu klausul yang menyebutkan, “Jika setelah proyek selesai Pihak Kedua merasa pakewuh, maka proyek akan diulang lagi dari awal”?
Sejak itu, sebenarnya saya berjuang keras untuk melawan rasa pakewuh itu. Tapi ternyata saya tetap tidak bisa lepas sepenuhnya.
Misalnya saja saat menerima undangan-undangan sebagai pembicara. Saya tahu, dunia menulis dicitrakan dekat dengan hal-hal yang intelektuil, dan yang intelektuil seringkali dianggap agak-agak sakral. Karena sakral, ia tak boleh berjalan seiring dengan perkara duniawi semacam uang. Walhasil, pembicara dalam forum-forum kepenulisan tidak pantas menanyakan honor, apalagi bertanya di depan. Begitu kelaziman diam-diam yang selama ini berjalan.
Otak kognitif saya ingin melawan itu. Saya nggak mau jadi penulis miskin. Tetapi, tiap kali saya mau menanyakan perkara duniawi seperti itu, selain segera terbayang betapa kehidupan akhirat kelak lebih hakiki dan kenikmatan di sana lebih kekal dibanding sekadar amplopan pembicara, yang pasti rasa pakewuh itu menyerang-nyerang hati saya.
Dengan songong selalu saya katakan kepada kawan-kawan saya sesama penulis bahwa sudah saatnya tradisi apresiasi yang rendah kepada profesi penulis itu dihentikan. Caranya ya dengan membangun tradisi baru, misalnya memosisikan kerja profesional kita jelas di depan. Maka, tak perlu ragu untuk bicara hak honor dulu sebelum memulai setiap kewajiban.
Tetapi jujur saja, meski saya sesongong itu, giliran berkomunikasi dengan panitia acara-acara, rasa pakewuh itu tak pernah berhenti menghantui saya. Bagaimana kalau mereka jadi salah tingkah? Bagaimana kalau ternyata mereka tak punya anggaran? Bagaimana kalau mereka jadi pakewuh sama saya gara-gara mereka cuma punya bajet untuk plakat dan piagam ucapan terima kasih? Aduh.
“Ya sudah, disyukuri saja,” kata saya kepada istri. “Masih punya rasa pakewuh itu anugerah. Artinya kita masih punya sisi mempertimbangkan hati dan perasaan orang lain, to.”
Begitulah akhirnya komentar pamungkas saya lontarkan kepada istri saya. Dan tiba-tiba, saya merasa bahagia karena jadi orang yang gampang pakewuhan.
Saya menuliskan curhatan ini di kamar sebuah hotel di Bandung. Sebenarnya saya merahasiakan kedatangan saya ke kota ini, karena jadwal pekerjaan begitu padat dan sepertinya tidak akan ada waktu yang cukup untuk nongkrong bercengkerama bersama teman-teman. Tapi pagi tadi ada seseorang yang mencium gelagat kehadiran saya, men-japri saya, lalu bilang, “Gotcha!”
Aduh, saya pakewuh sekali. Rasanya mustahil saya mengabaikan teman-teman, sementara setahun sekali pun belum tentu saya datang ke sini. Mungkin tetap saja saya akan gagal menjumpai mereka, tapi diam-diam saya bahagia dan mensyukuri rasa pakewuh yang tak henti merongrong kemerdekaan perasaan saya.
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)