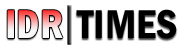Mi’raj Qalbu

Jakarta –
Pemahaman kita selama ini mi’raj diartikan sebagai perjalanan lahir dan batin Nabi dari Masjid Haram ke Sidratil Muntaha setelah transit di Masjid Aqsha, sebagaimana disebutkan dalam ayat: “Maha Suci Allah, yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Al Masjidil Haram ke Al Masjidil Aqsha yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami”. (Q.S. al-Isra’/17:1).
Cara pandang kita terhadap ayat tersebut masih lebih menekankan aspek denotative-eksoterik. Terbukti peringatan Isra’ Mi’raj yang secara rutin diperingati dan dirayakan dengan tanggal merah yang meliburkan seluruh sekolah, kampus, dan kantor-kantor secara nasional.
Isra’ Mi’raj lebih diperkenalkan sebagai peristiwa makrokosmos berupa perjalanan Nabi dari Masjid Haram ke Masjid Aqsha, Palestina, sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian Rasulullah pulang membawa oleh-oleh berupa shalat lima waktu.
Pembahasan ini samasekali tidak salah namun tidak ada salahnya jika Isra’Mi’raj juga difahami sebagai upaya untuk meng-up grade qalbu kita yang tadinya kasar menjadi lembut dan yang tadinya selalu berorientasi kepada hal-hal duniawi ke hal-hal spiritual ukhrawi.
Allah Swt memperjalankan hambanya di malam hari (lailan), bukan di siang hari (naharan). Kata lailah mempunyai beberapa makna. Ada makna literal berarti malam, lawan dari siang. Ada makna alegoris seperti gelap atau kegelapan, kesunyian, keheningan, dan kesyahduan; ada makna anagogis (spiritual) seperti kekhusyukan (khusyu’), kepasrahan (tawakkal), kedekatan (taqarrub) kepada Ilahi. Dalam syair-syair klasik Arab, ungkapan lailah lebih banyak digunakan makna alegoris (majaz) ketimbang makna literalnya, seperti ungkapan syair seorang pengantin baru: Ya lalila thul, ya shubh qif (wahai malam bertambah panjanglah, wahai subuh berhentilah). Kata lailah di dalam bait itu berarti kesyahduan, keindahan, kenikmatan, kehangatan, ketenangan, kerinduan, keakraban, sebagaimana dirasakan oleh para pengantin baru, yang menyesali pendeknya malam.
Dalam syair-syair sufistik juga lebih banyak menekankan makna anagogis kata lailah. Para sufi lebih banyak menghabiskan waktu malamnya untuk mendaki (taraqqi) menuju Tuhan. Mereka berterima kasih kepada lailah (malam) yang selalu menemani kesendirian mereka. Perhatikan ungkapan Imam Syafi’: Man thalab al-ula syahir al-layali (barangsiapa yang mendambakan martabat utama banyaklah berjaga di waktu malam). Kata al-layali di sini berarti keakraban dan kerinduan antara hamba dan Tuhannya.
Malam hari memang menampilkan kegelapan, tetapi bukankah kegelapan malam itu menjanjikan keheningan, kesenduan, kepasrahan, kesyahduan, kerinduan, kepasrahan, ketenangan, dan kekhusyukan? Suasana batin seperti ini amat sulit diwujudkan di siang hari. Seolah-olah yang lebih aktif di siang hari ialah unsur rasionalitas dan maskulinitas kita sebagai manusia dan ini mendukung kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi. Sedangkan di malam hari yang lebih aktif ialah unsur emosional-spiritual dan femininitas kita dan ini mendukung kapasitas kita sebagai hamba (‘abid).
Dua kapasitas manusia ini menjadi penentu keberhasilan hidup seseorang. Sehebat apapun prestasi sosial seseorang tetapi gagal membangun dirinya sebagai hamba yang baik maka itu sia-sia. Hal yang sama juga terjadi pada sebaliknya. Kekuatan malam hari untuk memikrajkan qalbu ditandai dengan penetapan waktu shalat itu lebih banyak di malam hari. Hanya shalat dzuhur dan Ashar di siang hari, selebihnya di malam hari seperti shalat Magrib, Isya, tahajud, witir, tarwih, fajr, shubuh. Malam hari memiliki semacam The Power of night yang bisa memikrajkan qalbu setiap orang.
(lus/lus)
Mi’raj Qalbu