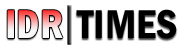Mengaktifkan Nurani Kemanusiaan

Jakarta –
Sejak beberapa waktu menjelang bulan puasa Ramadhan, tiap mata kita dengan mudah menyaksikan spanduk-spanduk di sudut-sudut jalan, iklan-iklan yang bertebaran lewat video, maupun capture di media sosial. Semua dengan nada sama kerap menyatakan “Selamat Datang Tamu Agung”, dengan varian redaksi yang bermacam-macam.
Implisit dalam ucapan tersebut adalah sebuah asumsi bahwa kita umat Islam sedang akan kedatangan tamu istimewa.
Jika Ramadhan adalah tamu, berarti kita yang adalah tuan rumahnya. Fenomena ini setidaknya menggambarkan betapa terhormatnya kedatangan bulan yang satu ini. Lazimnya, dalam sebuah perjamuan, sang tuan rumah menghidangkan aneka macam menu makanan, pelayanan yang prima, hingga segenap fasilitas yang dapat digunakan oleh sang tamu. Dan pula tentu saja, sang tuan rumah bakal amat simpati dan hormat bila yang datang tersebut penuh dengan sikap sopan santun.
Berjumpa dengan Ramadhan, hidangan dan fasilitas apa yang telah kita siapkan? Bukankah justru kita yang tengah memasuki bulan ini, dan bukankah kita yang tengah dijamu dan dimanja dengan sekian hidangan dan fasilitas? Berlipatnya pahala amal kebaikan, ampunan tiada batas, dan malam dengan nilai lebih dari seribu bulan, dan bahkan hingga tidurnya dicatat sebagai ibadah. Maka, apa yang menjelaskan kita sebagai tuan rumah?
Tampaknya yang terjadi justru adalah sebaliknya. Bukan dia yang tamu, tapi kita. Kita bisa ada dan pergi, tapi Ramadhan selalu stand by menunggu tamunya. Adalah pasti tahun depan Ramadhan akan ada, tapi tidak jaminan tahun depan kita masih ada. Sementara itu, tentu saja Ramadhan akan sangat bahagia jika kita datangi rumahnya dengan penuh kesopanan, penghargaan, dan ketulusan. Memasukinya dengan hati ikhlas serta mentaati aturan serta etika yang berlaku di dalamnya.
Merasakan Kemanusiaan
Tapi, bukan janji berlipat pahala yang menjadikan bulan ini istimewa, melainkan materi pembelajarannya: kemanusiaan. Kita diminta untuk menahan diri dari segala bentuk kenyamanan, kemewahan, dan keberlebih-lebihan. Tegasnya, kita dituntut menahan diri.
Selama ini, pendapatan masing-masing kita adalah pemisah yang amat tajam. Pendapatan yang berbeda melahirkan gaya hidup berbeda. Tentu saja, yang tak berkecukupan nyaris tak pernah dapat bergaya. Fenomena ini menjadi semacam hukum sejarah bagi manusia. Fakta-fakta sosial kita mencatat dengan gamblang mengapa satu orang bisa membunuh orang lain, satu kelompok bisa menindas kelompok lain, beberapa anak bisa berbeda fasilitas pendidikan dengan sejumlah besar anak lain.
Sejauh ini pangkat-jabatan adalah garis demarkasi antara si rakyat dan si raja. Si raja bisa hidup dengan fasilitas negara dan si rakyat harus berjuang sendiri meraih kecukupan hidupnya. Negara yang didesain menyatukan kita secara politik, dalam skala kebudayaan justru menjadi pagar yang menciptakan jarak antara rakyat dan pejabatnya. Maka, pendapatan dan pangkat-jabatan menjadi garis pemisah antaranak cucu Adam.
Lantas, di manakah yang disebut kemanusiaan? Yang bahkan kita jadikan dasar negara ini (sila ke-2: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).
Ramadhan ingin berkata pada kita, bahwa rasa lapar itu ada, dan dialami sejumlah besar manusia yang hidup di bumi ini. Dan bahwa ketidakadilan adalah musuh besar kemanusiaan. Jika kita merasa nikmat kala berbuka puasa dengan menyantap hidangan lezat depan mata, bukankah itu menandakan betapa menahan lapar itu cukup berat? Sehingga keluar dari padanya adalah kenikmatan.
Bagaimana dengan mereka yang setiap harinya bahkan tak bisa makan lantaran tak punya apa-apa untuk dibeli dan dimakan? Kemanusiaan adalah nilai yang amat mahal yang diajarkan bulan ini. Bukan sekadar soal tak makan dari subuh hingga maghrib, tapi rasa kejiwaan akan kemanusiaan itu sendiri. Kita memang amat kurang berbagi dan makin kurang lantaran sistem sosial kita terdesain untuk tidak saling berbagi.
Tak berhenti soal makan, tapi menahan diri dari banyak berbual dan berkata-kata juga bagian penting ajaran puasa. Betapa banyak kata yang terlempar dari mulut ini menyasar perasaan orang tak bersalah atau bahkan memicu perpecahan antarkelompok masyarakat, apalagi saat ini telah difasilitasi oleh media sosial.
Ramadhan mengajarkan kita sebagai tamunya bahwa kedamaian itu akan hadir jika kita belajar menahan diri untuk banyak berbual, banyak mengoceh dan melontarkan bola panas untuk membakar suasana. Kita mesti belajar menahan diri untuk tidak saling mencela dan melampiaskan kebencian dan kemarahan yang saling merugikan.
Menggapai Esensi
Secara fitrah manusia pasti menghendaki kebahagiaan pada dirinya. Sementara penderitaan adalah sesuatu yang sebisa mungkin dapat dihindari. Namun, makna kebahagiaan masing-masing orang bisa jadi berbeda bergantung cara pandangnya terhadap kehidupan. Boleh jadi satu orang berkeyakinan bahwa harta adalah sumber kebahagiaan sementara yang lain tidak.
Namun jika memang setiap masing-masing menghendaki kebahagiaan sementara kebahagiaan tersebut diraih dengan memberangus kebahagiaan orang lain atau di atas penderitaan orang lain, apakah hal demikian merupakan kebahagiaan yang hakiki? Bukankah itu bertentangan dengan prinsip sebelumnya bahwa tiap orang berhak untuk bahagia?
Ramadhan hadir untuk berbagi nasib dan berbagi rasa. Setiap orang diajak untuk mengaktifkan nurani kemanusiaannya, dengan mengendalikan diri dari banyak hal yang membuatnya terasing dari dirinya sendiri.
(mmu/mmu)
Mengaktifkan Nurani Kemanusiaan