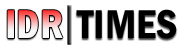Ketika Tahi Ayam Naik ke Meja Hijau

Jakarta –
Konflik-konflik kecil dan terlihat remeh dalam hubungan bertetangga merupakan cermin melemahnya keampuhan “mekanisme sosial” berupa jalur kekeluargaan. Tetapi membawa sebuah perseteruan ke jalur hukum adalah satu tanda. Bahkan mungkin sebagai pencapaian: kita bukan lagi masyarakat yang bimbang.
Belum lama ini, khalayak dihebohkan berita tentang seorang warga yang membangun pagar tembok karena jengkel sering menginjak tahi ayam milik tetangga. Akibatnya, tiap kali Wahyu Widodo pemilik ayam di sebuah desa Kabupaten Ponorogo tersebut ingin keluar-masuk rumahnya, ia harus melompati pagar tembok dengan bantuan kursi.
Mungkin soal tahi ayam ini memang bukan soal sepele; bukan sekadar jijik dan kesal berskala ringan. Ada agenda dan kepentingan yang lebih besar dari pihak-pihak yang bermusuhan. Faktanya, ia tidak selesai dengan “mekanisme sosial” semata. Macet dalam rembuk antarpribadi, gagal di tingkat RT, tidak mampu dimediasi aparat desa. Kemudian menempuh jalan dengan mencari menang-kalah di meja hijau.
Bahkan setelah diputuskan oleh pengadilan, belum juga ada eksekusi pembongkaran pagar, karena kabarnya ingin dilanjutkan dengan naik banding. Telanjur viral, kabar terakhir pagar dirobohkan setelah Bupati turun tangan.
Menjaga Harmoni
Selama ini, kita selalu meyakinkan diri bahwa tersedia modal-modal sosial yang melimpah ruah untuk menjaga harmoni dan keselarasan. Kita mengggantungkan harapan bahwa nilai-nilai keguyuban dan kekeluargaan selalu ready stock, minimal di pedesaan tradisional. Ana rembug, dirembug.
Saya ingat petuah sesepuh di kampung saya, saat ada warga yang membangun pagar tinggi sampai fasad rumahnya justru tak terlihat. “Tetangga adalah keluarga yang paling dekat. Janganlah bangun pagar tinggi-tinggi, karena yang membuatmu aman adalah tetanggamu. Tetanggamu itulah pagarmu.”
Di desa inilah, kita berharap hidup bertetangga dengan harmonis. Sehingga tak perlu “membeli” tetangga, seperti pepatah Rusia “jangan membeli rumah, tetapi belilah tetangga.” Namun, bukankah kasus-kasus sengketa antartetangga juga terjadi di desa, termasuk kasus tahi ayam?
Bisa jadi, perumahan yang dibangun para pengembang di perkotaan justru lebih tertib. Aman dari tahi ayam. Ah, tidak juga! Sebab “tahi ayam” itu bisa berwujud kebisingan musik, anjing yang terus menggonggong, kasus parkir sembarangan, pohon yang daunnya menyeberang, dan silakan tambah daftarnya sendiri yang pernah terjadi di lingkungan atau Anda malah mengalaminya sendiri.
Sambil berharap tuah jalan kekeluargaan, kita tumbuh menjadi masyarakat yang menghindari sengketa, emoh ribut dan gemar mencari kompromi. Kesal harus rapat disimpan, menahan nafas dalam-dalam sambil berkata, “Sing waras ngalah.” Jalur hukum? Eits, nanti dulu! Kita bukan tipe masyarakat yang mencari penyelesaian (hukum).
Memang sih, “main hakim sendiri” di media sosial itu lumrah saja. Tetapi kok nyaris tidak terdengar penyataan, “Anda berada di jalan yang benar. Perjuangkan kebenaran walau aromanya seperti tahi ayam, bahkan jika perlu sampai tingkat banding.” Kenapa sih, tidak kita apresiasi saja warga yang membawa perkara level tahi ayam ini naik ke meja hijau?
Mungkin benar, menumpuknya soal-soal antartetangga menandakan rapuhnya hubungan komunal. Lha, bukannya institusi tradisional memang sudah lelah menampung konflik macam ini? Lalu harus bagaimana jika aturan-aturan informal tetap tidak ampuh membawa perkara selesai dengan jabat tangan?
Di Tangerang Selatan pernah ramai gugatan hukum gara-gara pohon tetangga daunnya menyeberang. Di Pekanbaru, tetangga yang membangun pagar seng di rumahnya sendiri dianggap mengganggu pemandangan, cekcok sampai di pengadilan. Di Jakarta Utara, dua tetangga berseteru di depan hakim, yang satu digugat karena meludah yang lain dituduh menghina. Sebuah bukti bahwa kita sudah tumbuh menjadi masyarakat yang tidak lagi bimbang.
Namun, persoalan zaman kiwari ternyata nyaris masih sama dengan 50 tahun yang lalu. Seperti diungkapkan oleh Daniel S Lev, Indonesianis asal Amerika Serikat yang meneliti budaya hukum di Indonesia pada tahun 1970-an. Ia takjub dan geleng-geleng kepala tatkala menghadapi suatu kasus hukum, ia justru mendapat nasihat dari temannya yang hakim untuk menempuh jalan damai. Ini tercatat dalam tulisan tentang Perilaku Gugat-Menggugat oleh Satjipto Rahardjo.
Jadi, jangan heran, seperti kasus terbaru di Sragen, antartetangga bersengketa hukum gara-gara batas tanah selisih satu ubin 30 senti. Perhatikan pendapat Ketua Advokat setempat, “Seharusnya ini bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan.” Lha, warga ke meja hijau ingin menguji. Melegitimasi kemenangan secara elegan. Berkompetisi sesuai kasta orang modern.
Lalu kapan saatnya warga boleh mendapat apresiasi dan dibenarkan untuk mengambil jalan hukum? Ke mana nasib masyarakat sadar hukum yang dikampanyekan para elit melek hukum sejak lama?
Ini era masyarakat yang tak lagi bimbang. Masyarakat yang sadar, tidak ada jalan putar balik, dari patembayan menjadi paguyuban lagi sesuai konsep dasar sosiologi ala Ferdinand Tonnies. Bukan lagi masyarakat berwatak seperti “Lebai Malang” yang bimbang mendatangi undangan kenduri di hulu sungai atau harus hilir sungai. Malangnya, dia tidak mendapatkan apa-apa. Hendak mengunduh damai, malah yang dipanen kekesalan dan konflik yang tersimpan lagi berkepanjangan.
Warga yang menempuh jalan “ketok palu” adalah bukti, mereka lepas dari kutukan “skizofrenia sosial” yang kerap disematkan secara sinis oleh para pakar. Tidak lagi berkepribadian setengah-setengah, antara pemuja nilai-nilai lama kekeluargaan atau penganut nilai-nilai baru yang formal.
Jangan Kagetan
Harusnya kita ini jangan kagetan. Siapa tahu, saat asyik ngopi di teras rumah, mencoba toleran dengan suara sangar knalpot motor modifikasi berjenis dua tak milik tetangga yang selalu dipanaskan mesinnya kelewat lama, tahu-tahu Anda menerima surat panggilan dari pengadilan untuk menyelesaikan perkara tentang istri Anda yang suka keluar rumah beli sayur dengan daster merah. Gara-gara tetangga Anda seorang erythrophobia, fobia warna merah.
Saat kita merasa menjadi korban, pada waktu yang sama siapa tahu kita sebagai tersangkanya. Inilah era menumpuknya “tahi ayam” di meja hijau. Apa salahnya diselesaikan secara hukum? Tentu, tidak dengan berbelit-belit atau berlarut-larut. Siap menang, siap menerima jika dikalahkan. Sambil masyarakat belajar “inilah proses keadilan disiapkan, dimasak, dihidangkan dan dinikmati.”
Selain itu, dengan menempuh jalan jalan ketok palu, masalah akan menjadi terang. Mengerem spekulasi, meluruskan komentar serta opini yang terlalu jauh melompati pagar proporsinya. Bupati pun tidak harus repot-repot melerai pertengkaran antartetangga. Kasus seperti ini jelas berpotensi mencoreng wajah dan identitas wilayah yang dipimpinnya.
Toh, merebaknya jumlah perkara antarwarga di pengadilan, pesan Francis Fukuyama dalam Guncangan Besar, jangan buru-buru diartikan sebagai susutnya modal sosial. Sebaliknya, bisa menjadi indikator positif dari modal sosial. Menjadi bukti meningkatnya inisiatif warga memperbaiki perselisihan di antara mereka sendiri daripada bergantung pada wewenang hierarki.
Pemerintah tak mungkin memantau dan mengawasi segala jenis persoalan warga, bukan? Apa iya, Bupati atau Gubernur yang tengah sibuk memimpin Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di wilayahnya lagi-lagi harus turun tangan jika muncul sengketa antartetangga?
Atau, jangan-jangan kita memang sengaja menyimpan dan memelihara banyak soal dan masalah agar tak pernah selesai! Jadi, sesungguhnya siapa yang bimbang?
Makhsun Bustomi pekerja sosial, magister sains dalam manajemen sumber daya manusia dan aktif dalam litbang dakwah LDNU di Kota Tegal
(mmu/mmu)
Ketika Tahi Ayam Naik ke Meja Hijau