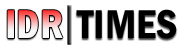Kemungkinan Terburuk Hanyalah Memulai Kembali

Jakarta –
Sepuluh ribu untuk setahun. Demikian tukang koran di lapak langganan saya di dekat Pasar Pondok Labu selalu berkata setiap kali saya membeli kalender baru pada akhir tahun. Walaupun kejadiannya hanya setahun sekali, tapi saya ingat betul kalimat bernada seloroh dan memang dimaksudkan untuk melucu itu selalu dia ucapkan, sama persis, dan sebagai basa-basi balasan saya pun tertawa.
Ada yang tak pernah berubah dalam hidup hidup ini. Apa yang kita ucapkan, kelakar kita, dan mungkin cara kita menjalani hidup itu sendiri. Ada yang masih berada di tempat yang sama setelah waktu terus berlalu, seperti karang di tepi pantai yang abadi walau setiap hari digempur ombak dan terkikis, tapi tidak pernah hancur dan lenyap, bertahan dengan caranya sendiri.
Lelaki penjual koran dan buku teka-teki silang tersebut sudah berjualan di lapak di ujung pertigaan dekat pasar itu sejak pertama kali saya tinggal di Jakarta. Saya selalu membeli koran di tempatnya, minimal setiap hari Minggu. Ketika era koran mulai surut tahun-tahun belakangan, dia masih tetap berjualan, dengan jumlah tumpukan dagangan yang makin menyusut.
Beberapa eksemplar majalah lama yang sampulnya sudah lusuh juga dipajang, bukan untuk dijual, melainkan sekadar untuk “menuh-menuhin” lapak. Menjelang akhir tahun, dia menambah dagangannya dengan kalender. Saya selalu membeli yang berwarna putih polos, dengan angka-angka yang tercetak besar-besar, memuat cacatan waktu satu bulan dalam satu lembar. Kalender model lama yang sederhana, tanpa gambar, dan harganya murah.
Saya menurunkan kalender yang lama dan menggantinya dengan yang baru sambil merenung. Saya gulung kalender lama itu, seperti menggulung tahun yang akan ditinggalkan, sambil berbisik dalam hari, hidup hanyalah pergantian waktu; kita menggulung yang lama, untuk menatap yang baru, yang terentang di depan sana. Selebihnya semua mungkin akan sama saja. Setelah kalender baru terpasang di dinding, hidup akan berjalan seperti biasanya.
Setiap awal tahun kita merenungkan kembali hidup kita. Menghitung-hitung apa yang telah kita capai dalam setahun, dan membuat rencana-rencana baru, dengan harapan-harapan baru. Kita mengingat-ngingat, apa yang telah terjadi dalam setahun yang baru saja kita tinggalkan. Kali ini, kita mungkin merasa lebih hampa dari biasanya. Ada yang meninggalkan tahun yang baru saja berlalu itu dengan sumpah serapah. Banyak hal buruk terjadi.
Tahun itu, ada yang bisnisnya hancur; ada yang kehilangan pekerjaan; ada yang memulai usaha baru. Ada pula yang memutuskan untuk pulang ke kampung halaman dengan perasaan kalah. Ada yang bertahan dengan bekerja dari rumah. Ada yang kedengarannya menyenangkan: pindah ke Ubud, dan bekerja dari sana. Ada yang sakit, ada yang kehilangan anggota keluarga, teman, dan orang-orang terdekat yang disayang.
Saya memandangi kalender yang putih bersih dengan angka-angka yang tertata rapi. Saya elus ujungnya yang masih agak melengkung karena tadinya tergulung. Saya masih memegangi gulungan kalender lama, yang sudutnya geripis karena dicakari kucing yang suka naik ke atas meja. Hari terakhir menjelang pergantian tahun terasa sangat panjang oleh bayangan-bayangan, ingatan-ingatan, dan renungan-renungan yang sambung-menyambung tiada habisnya.
Kata “bersyukur” mendadak menjadi begitu berarti, dan mungkin untuk pertama kalinya maknanya benar-benar kira resapi. Sebuah harian nasional, pada hari terakhir sebelum tahun berganti itu, memasang headline bernada ungkapan perasaan yang lega: 2020, Bersyukur Mampu Bertahan. Semua orang sepertinya punya pikiran yang sama, bahwa bertahan saja sudah merupakan sebuah keistimewaan, yang perlu kita syukuri.
Menjelang sore, saya duduk-duduk di lapo di Pusat Kuliner Toba yang ada di mall di Jakarta Selatan. Saya makan ombus-ombus kesukaan saya, menegak minuman Cap Badak, sambil mendengarkan organ tunggal yang ditingkahi petikan gitar akustik, mengiringi sepasang penyanyi, laki-laki dan perempuan, melantunkan lagu-lagu memori dalam irama dangdut yang riang.
Bahagia itu nggak perlu banyak duit, yang penting semangat menyambut tahun baru, kata si penyanyi pria yang berusia separuh baya. Lalu bersama pasangan duetnya, dia menyanyikan sebuah lagu Melayu klasik: hasrat hati hanya sekedar bertanya/ mengapa wajahmu selalu berbeda/ sehingga lenyap keindahan kurasa/ aduhai apakah gerangan sebabnya….
Setiap pergantian lagu, si penyanyi pria mengulang ucapannya bahwa kebahagiaan itu tidak harus punya uang banyak, yang penting semangat. Kali ini, dia menambahkan, “Banyak yang sudah pergi ke Bali untuk menyambut dan merayakan tahun baru. Kita di sini saja, bahagia dengan berdangdut ria.” Lalu, terlantunlah lirik-lirik yang membuat badan spontan ikut bergoyang: Sekuntum mawar merah/ yang kau berikan kepadaku/ di malam itu….
Untuk sesaat saya lupa bahwa saya tengah berada di ujung hari, pada hari terakhir tahun yang akan segera berganti. Setelah itu, suasana mendadak berubah menjadi melow, seiring dengan duet penyanyi bersuara bagus itu membawakan lagu dengan lirik yang meratap-ratap: kau datang dan pergi sesuka hatimu/ oh, kejamnya dikau/ teganya dikau padaku….
Tanpa sadar saya ikut menyanyi. Hati saya menjadi rawan. Saya terlempar kembali ke masa kini dan sadar, di sinilah saya sekarang, di pengujung tahun, makan ombus-ombus, dan minuman Cap Badak saya sudah tandas. Tenggorokan saya tercekat. Waktu datang dan pergi, kadang-kadang terasa begitu kejam dan tega. Apa yang akan terjadi besok? Peristiwa dan pengalaman apa yang akan menggulung kita setahun ke depan?
Lorong beratap rendah di basement mall itu kini hening. Penyanyi dan pemain musik beristirahat, makan biskuit dan menikmati minuman. Para pengunjung dan penjaga lapo tenggelam dalam layar handphone-nya masing-masing. Hari sudah akan malam. Waktu seperti menghitung mundur dirinya sendiri, untuk undur selama-lamanya, dan digantikan dengan tahun yang baru.
Saya mengedarkan pandangan ke sekeliling, dan dalam keheningan itu saya melihat, harapan baru semakin dekat, bukan karena saya yakin, tapi semata-mata karena kita terbiasa berpikir bahwa tahun baru selalu membawa harapan baru. Dan, kali ini, rasanya-rasanya saya ingin sekali mendekap erat pikiran itu. Memangnya apa sih yang selama ini masih tersisa kita miliki, kalau bukan harapan?
Tahun berganti, dan apapun bisa terjadi. Tahun yang datang selalu bisa lebih baik dibanding tahun yang pergi, tapi bisa juga sama buruknya atau bahkan lebih buruk lagi. Tapi, memangnya kenapa? Bukankah hidup harus terus berjalan? Saya teringat satu larik dari sebuah lagu Mandarin. Kemungkinan terburuk hanyalah memulai kembali.
Kita selalu memasuki hari-hari di tahun yang baru dengan penuh harapan, tapi juga keraguan. Kita bisa bertahan lagi, dan melewatinya lagi. Kita bisa berhasil, tapi juga bisa gagal. Tapi, memangnya kenapa? Tidak ada yang buruk dari semua itu, karena yang kita perlukan hanyalah memulai kembali, lagi dan lagi.
Mumu Aloha wartawan, penulis, editor
(mmu/mmu)