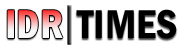Hukum dan Tsunami Revolusi Digital

Jakarta –
Revolusi industri adalah masa lalu. Dalam satu dekade terakhir, dunia digital berevolusi sangat cepat bak tsunami. Bila dalam revolusi politik kadang memakan anaknya sendiri, maka demikian juga dalam revolusi digital. Lalu di manakah keberadaan hukum agar dapat menghadirkan keadilan bagi rakyat Indonesia?
Sejak Ratu Elizabeth II mengirimkan email pertama pada 26 Maret 1976, dunia digital terus mengalami perkembangan pesat. Dan, dalam satu dekade terakhir revolusi itu tidak terbendung. Bak tsunami menghempaskan seluruh tatanan yang ada di depannya
Lihatlah Google. Kini tidak hanya menguasai layanan email, tetapi juga algoritma. Tidak hanya menjadi panduan peta jalan, Google perlahan ikut menggerus platform pemesanan tiket/hotel. Sosial media juga berubah bak cendawan di musim hujan. Yang awalnya untuk fungsi sosial/eksistensi pemilik akun, kini bergeser menjadi alat propaganda politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Teranyar, media sosial berfungsi juga merangkap sebagai platform marketplace sehingga pemerintah yaitu Menteri Perdagangan dan Menkomonfo melakukan sejumlah larangan.
Revolusi digital juga menumbuhkan konglomerasi baru di dunia. Kripto salah satunya. Sistem keuangan konvensional tercabik-cabik.
Sejarah Berulang
Pada 195 SM, Plautus membuat sebuah karya berjudul Asinaria dan muncul istilah homo homini lupus, kependekan dari homo homini lupus est, yang dalam terjemahan bebasnya yaitu manusia adalah serigala bagi sesama manusia. Istilah ini sebagai kritikan atas homo homini socius, manusia adalah teman bagi sesamanya.
Sejarah berulang. Kini era revolusi digital melahirkan homo homini lupus gaya baru. Platform raksasa asing memakan semua platform dan menguasai dari hulu ke hilir. Tidak hanya menguasai entitas bisnis, juga menguasai pola pikir rakyat Indonesia dengan algoritma digital.
Di sektor ekonomi, pelaku pasar konvensional dipaksa harus bertarung dan masuk ring digital. Namun ring digital telah dikuasai segelintir kartel platform dan pemain. Si kaya melawan si miskin. Raksasa dunia melawan platform lokal.
Alih-alih melahirkan persaingan usaha yang sehat, tetapi malah melahirkan diskriminasi, pertandingan yang tidak seimbang. Mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi, rumus dasar diskriminasi adalah “Untuk hal yang sama tidak boleh dibedakan, untuk yang berbeda tidak boleh disamakan.”
Maka sangat tidak fair bila terjadi pertarungan David vs Goliath tetapi negara diam saja dan hukum hanya menjadi penonton. Sehingga hukum negara harus hadir agar mencegah manusia digital menjadi serigala bagi manusia digital lainnya. Maka perlu pemberlakuan yang berbeda sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007:
“Bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.”
Negara Harus Hadir
Dalam era disrupsi ini, negara harus hadir menata kehidupan baru. Hukum harus menjadi tools of engineering. Negara bukan hanya “penjaga malam” (nachtwachterstaat). Lewat hukum, negara harus berdaulat untuk memajukan kesejahteraan umum sebagai amanat UUD 1945. Lebih jauh lagi, hukum harus memastikan sila kelima Pancasila harus hadir yaitu Keadilan Sosial Bagi Masyarakat.
Langkahnya yaitu mengubah secara revolusioner UU terkait yang bersentuhan dengan dunia digital. UU Pers harus disegarkan agar melindungi insan pers pada khususnya berupa perlindungan hak cipta dan kekayaan intelektual dan informasi yang sehat pada umumnya.
Beriringan dengan itu, perlu disegarkan kembali UU Hak Cipta dalam tempo sesingkat-singkatnya. Di mana paltform digital dalam bentuk user generated content (UGC) menjadi media pembajakan yang terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mematikan ide dan karya intelektual masyarakat.
Dalam grand design yang lebih besar, UU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat harus segera direvisi untuk memastikan sebuah entitas bisnis tidak mengusai segala lini platform. Negara juga harus menjaga kedaulatan digital di bidang media sosial tanpa harus merenggut kebebasan berpikir, berpendapat, dan berbicara warga negara sebagai amanat UUD 1945.
Kebocoran data Facebook pada 2018 menjadi bukti gagalnya hukum mencegah korban tsunami digital. Sebagaimana mengutip putusan Pengadilan Tinggi Jakarta soal gugatan class action warga melawan Facebook:
“Terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, sebenarnya apa yang dilakukan pembanding, semula Penggugat I, merupakan suatu hal yang mulia dalam arti mengusahakan terlindunginya kepentingan masyarakat atau kepentingan umum dan sela itu itu dari pada itu juga untuk lebih meningkatkan tanggung jawab moral pihak yang harus bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah terlindunginya data pribadi pengguna Facebook.”
UU Nomor 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) harus segera diterapkan, meski belum ada Peraturan Pemerintah. Silang sengketa siapa yang berwenang menjadi Komisi PDP tidak bisa menunggu sampai Oktober 2024 sebab kebocoran demi kebocoran terus terjadi. Salah satu yang terkini adalah kebocoran data paspor.
Saat ini UU Hak Cipta ini sedang diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Namun sepertinya terlalu berat dan terlalu luas bagi Mahkamah Konstitusi memperbaiki dan membuat tatanan baru dunia digital lewat putusannya. Oleh sebab itu, pandemi digital di atas menjadi tantangan bagi rezim baru 2024 – 2029 untuk menyudahinya. Yaitu, DPR baru dan presiden baru membangun sebuah ekosistem yang sehat dan fair serta berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Andi Saputra advokat
(mmu/mmu)