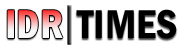Urgensi Transformasi Pengelolaan Hutan Jawa

Jakarta –
Terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 39 tahun 2017 tentang Perhutanan Sosial di Wilayah Kerja Perum Perhutani merupakan terobosan baru praktik perhutanan sosial di Pulau Jawa. Peraturan menteri ini membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat dalam mengakses dan mengkontrol pengelolaan hutan. Namun demikian, kebijakan ini masih belum membuka akses dan kontrol yang lebih luas pada tipologi lain yang terdapat di hutan Jawa.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa terdapat berbagai macam tipologi konflik agraria kehutanan. Salah satu contohnya di Desa Kedungasri, Banyuwangi. Di desa ini, setidaknya terdapat empat tipe konflik agraria kehutanan yang membutuhkan model penyelesaian yang berbeda-beda. Tipe pertama, “hutan” yang di dalamnya terdapat pemukiman permanen, pekarangan, tegalan, dan persawahan.
Berdasarkan buku Letter C milik Pemerintah Desa Kedungasri, seluruh wilayah Dusun Pondokasem seluas 70 hektar merupakan tanah milik masyarakat. Letter C merupakan catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah pada zaman kolonial, tapi bisa juga digunakan sebagai alat bukti permulaan untuk memperoleh suatu hak atas tanah (Suparyono, 2008). Bahkan di tanah tersebut telah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).
Pada sisi lain, Perum Perhutani mengklaim wilayah tersebut sebagai kawasan hutan negara dengan fungsi Hutan Produksi. Untuk tipe pertama ini, masyarakat mengajukan agar lahan tersebut masuk dalam skema Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Kedua, tanah yang berada di pinggir hutan mangrove. Awalnya wilayah tersebut dipenuhi dengan tanaman jati. Namun, pada tahun 2000 terjadi penebangan hutan yang tidak terkendali sehingga membuat hutan tersebut gundul. Sejak saat itu, masyarakat mengolah dan memanfaatkan tanah tersebut untuk pertanian sawah dan palawija. Terhadap tipe kedua ini, masyarakat mengusulkan agar hutan tersebut dikelola dengan skema Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHPS)
Ketiga, tanah yang masih terdapat tanaman kehutanan yang di sela-sela tanaman utamanya oleh masyarakat diolah dan dimanfaatkan untuk tanaman pangan. Oleh masyarakat, tanah ini akan diajukan izin Kemitraan. Keempat, tanah yang berada pada kawasan hutan lindung. Pada 1980, di tanah ini terdapat hutan mangrove alam yang kondisinya bagus tetapi lambat laun hutan mangrove tersebut rusak. Pada 2000-2004, masyarakat berupaya merehabilitasi lahan seluas 170 ha.
Pada 2010, pemerintah desa, masyarakat, serta pemerintah pusat melakukan rehabilitasi atas lahan tersebut. Saat ini, pemerintah Desa Kedungasri dan kelompok masyarakat mempromosikan wisata mangrove dan mengajukan areal itu untuk dikelola sebagai hutan lindung dan wisata desa.
Selain contoh di atas, dalam riset ini juga ditemukan bahwa pada 7 (tujuh) desa di 5 (lima) kabupaten di Jawa Tengah dan Jawa Timur juga mempunyai tipe-tipe konflik agraria kehutanan yang beragam dan dalam hal ini masing-masing desa merumuskan model reform yang harus dilakukan dan hasilnya masing-masing desa berbeda-beda.
Desa Sabrang di Jember memiliki tipologi konflik yang menghasilkan empat skema sekaligus yaitu TORA, Hutan Desa, IPHPS, dan Kemitraan. Besuki dan Tenggangrejo (Tulungagung) mengajukan IPHPS dan Kemitraan. Ngrandu (Trenggalek) mengajukan TORA, IPHPS, dan Kemitraan. Sedangkan Timahan (Trenggalek) hanya mengajukan TORA. Agak berbeda dengan lainnya, Desa Grugu (Cilacap) yang konfliknya menuntut adanya pengembalian lahan kembali ke desa yang dulu dihilangkan karena kasus DI/TII pada 1950-an dan PKI pada 1965-an.
Berdasarkan hal di atas, maka terdapat beberapa rekomendasi dalam penyelenggaraan implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) di Jawa. Pertama, pemerintah seharusnya memperhatikan usulan masyarakat sesuai dengan tipologi sosial/ sejarah dan fisik dalam kelola hutan. Kedua, pemerintah pusat membuat regulasi yang memungkinkan adanya skema Hutan Desa di Jawa untuk percepatan RAPS melalui Izin Pemanfaatan Hutan Milik Desa (IPHMD)
Restorasi Ekologi
Izin Pemanfaatan Hutan Milik Desa (IPHMD) adalah salah satu bagian dari RAPS yang meletakkan desa sebagai subjek hukum. Secara gagasan, pemberian hak pengelolaan hutan negara kepada desa adalah sebagai bentuk restorasi ekologi, sosial, dan ekonomi perdesaan. Secara teknis, hak pengelolaan desa adalah sebuah hak yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah kepada pemerintah desa berupa aset tanah dan hutan. Hak tersebut diwujudkan kedalam bentuk sertifikat atas nama pemerintah desa.
Prinsip utama proses transfer hutan dari Perhutani kepada desa adalah dalam rangka pemanfaatan sumber daya untuk kepentingan seluruh masyarakat desa. Untuk itulah transfer kelola hutan memperjelas posisi desa sebagai subyek hukum dalam bentuk pengalihan aset yang sebelumnya dikelolakan oleh Perhutani menjadi pengelolaan oleh desa. Selanjutnya, pengelolaan hutan sebagai aset desa dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan musyawarah desa.
Lantas, mau di kemanakan Perhutani yang selama ini diberi mandat pengelolaan hutan oleh negara? Setidaknya terdapat dua model yang bisa diimplementasikan. Pertama, Perhutani melakukan transformasi dari perusahaan yang mengelola hutan menjadi hanya mengelola tata niaga kehutanan. Kedua, menempatkan para pegawai Perhutani pada posisi seperti: mandor sampai mantri menjadi bagian dari masyarakat yang mendapatkan hak kelola desa; asisten Perhutani sampai dengan pegawai Perhutani pusat dapat ditempatkan di BUMN lain.
Upaya melakukan perubahan tata kelola kehutanan di Jawa ini sesungguhnya merupakan ikhtiar seperti halnya bangsa ini telah mengupayakan terjadinya otonomi daerah sebagai bagian dari desentralisasi kekuasaan atau keberadaan UU Desa yang merupakan bukti tindakan revolusioner untuk mendistribusikan salah satu kekuatan fiskal dari pusat langsung kepada unit terdekat.
Dengan semakin dekatnya akses rakyat kepada hutan diharapkan akan terjadi pula proses transformasi dari “Hutan Kaya, Rakyat Melarat” (Peluso:, 2006) menjadi “Hutan Subur, Rakyat Makmur” (Hardiyanto, 2015). Selain itu, transformasi pengelolaan hutan Jawa ini bisa menjadi jalan untuk mengatasi krisis pangan pada masa pandemi.
Barid Hardiyanto bekerja di Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), anggota Koalisi Pemulihan Hutan (KPH) Jawa
(mmu/mmu)