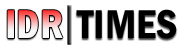Terjebak Rasa Sungkan Digital

Jakarta –
Sahabat saya, sebut saja namanya Uda Brewok, siang itu hepi sekali. Memang saya tidak melihat langsung raut wajahnya, tapi sangat bisa merasakannya dengan membaca tulisan yang dia unggah pada dinding Facebook-nya.
Jadi ceritanya, Uda Brewok mengagumi seorang ulama besar. Ulama ini bukan kaleng-kaleng, bukan produk Youtube atau tivi, dan kredibilitas ilmu serta kezuhudannya tak diragukan lagi.
Maka, betapa pantas Si Uda njenggirat kaget campur berbunga-bunga, ketika tiba-tiba melihat Mbah Kiai meminta pertemanan Facebook dengan dirinya!
“Ya Allah, aku sampai loncat dari kursi begitu melihat nama beliau di list pengajuan pertemanan. Tentu saja langsung kukonfirmasi. Sungguh ini berkah Jumat yang paling membahagiakan,” begitu tulisnya.
Terus terang, saya pun merasa iri dengan anugerah itu. Sampai kemudian saya melihat ada yang berubah pada tampilan Facebook si Uda.
Sebelum-sebelumnya, ada satu foto yang muncul berulang kali di dinding Facebook Uda. Foto itu agak bikin gimana, gitu. Saya sendiri yang menjepretnya, waktu kami sedang jalan-jalan ke Madura.
Dalam foto itu, Uda berposisi memandang ke sebuah titik. Sial buat dia, pose itu dilakukannya di depan sebuah toko pakaian dalam wanita. Maka, ketika saya memencet kamera diam-diam, sengaja saya posisikan Si Uda tengah memandangi jejeran kutang yang bergelantungan.
Foto itu pun dikopi oleh teman-teman lain, dan muncul berkali-kali dalam berbagai unggahan dan aneka caption. Bahkan akhirnya Uda Brewok sendiri berkali-kali mem-posting-nya ulang, dalam berbagai konteks, dalam banyak cerita.
Nah, tapi ternyata kisah itu ada akhirnya. Dan itu terjadi sejak FB Uda berteman dengan FB Mbah Kiai.
Foto legendaris itu memang kembali muncul. Ada cerita baru yang diunggah Uda, lagi-lagi dengan foto itu sebagai ilustrasi. Tapi yang mengejutkan, gambar kutang bergelantungan tak tampak lagi! Ya, Uda telah meng-crop foto itu, sehingga jadi jauh lebih sopan, jauh lebih civilized, dan tidak menciptakan efek kecanggungan yang bukan-bukan.
Saya menduga keras, semua itu terjadi karena Uda merasa sudah ada Mbah Kiai di daftar pertemanannya. Pasti setiap kali membuat unggahan, dia akan bertanya-tanya: Simbah lihat tidak ya? Waduh, kalau beliau lihat gimana? Jangan-jangan nanti aku kena tegur. Ah, enggak juga sih. Beliau bukan tipe seperti itu. Tapi gimana pun kan ya bikin aku malu. Belum lagi kalau Mbah Kiai kepingin komen di wall-ku, tapi malah batal cuma gara-gara enggan muncul di tempat yang sama dengan kutang-kutang koleksiku!
Semua itu memang cuma dugaan saya. Tapi dugaan itu terasa sangat masuk akal. Bahwa Mbah Kiai hanya salah satu saja di antara ribuan temannya, bahwa mayoritas teman online Si Uda pasti lebih cocok dengan selera foto kutangnya, itu memang benar. Tapi kekuatan kesungkanan di hadapan seorang ulama besar pasti berlipat-lipat lebih determinan daripada di depan ribuan temannya yang tak berguna itu.
Kesungkanan. Saya kira, itu sisi yang selama ini seolah dianggap tak lagi penting-penting amat dalam obrolan tentang komunikasi di alam digital. Manusia semakin impersonal, imaji anonimitas berkuasa, sikap-sikap impulsif yang mengabaikan batas-batas kepantasan sosial bermunculan dengan mudahnya.
Maka, klaim dan citra bahwa mayoritas masyarakat Amerika sangat demokratis, menjunjung tinggi HAM, sudah lupa dengan pandangan dunia yang berbasis warna kulit, dan sebagainya, termentahkan justru dengan telusuran big data yang mengungkap betapa lontaran-lontaran rasis di ruang digital sedemikian masifnya. Maka, populisme kanan menyembul ke permukaan. Maka, Trump waktu itu menang.
Setidaknya, itulah yang selintas diceritakan Seth Stephens-Davidowitz dalam bukunya Everybody Lies.
Di kiri-kanan kita sendiri, kita pun sempat melihat gelaran pertunjukan semacam itu dalam skala yang nyaris mengerikan. Teman lama yang bertahun-tahun tampak anteng-anteng saja tiba-tiba bisa menjadi beringas di akun Twitter-nya. Tetangga yang kita kenal sangat kalem mendadak kita pergoki menjadi predator yang sikat sana embat sini, seolah lupa bahwa yang mereka gebuki di alam online itu adalah kawan-kawan sendiri.
Lalu, di manakah perasaan sungkan itu tertinggal?
Ternyata, ia tercecer di ceruk-ceruk ruang yang sebenarnya masih tersisa untuk kemanusiaan kita. Big data memang ada, impersonalitas memang ada, tapi pertemanan dan sikap takzim masih menjadi realitas yang tak bisa kita abaikan begitu saja. Sering kali ia memang tercampakkan, tapi tiba-tiba di suatu pagi ia menjadi pertimbangan tunggal saat kita ingin melontarkan celetukan di layar HP yang bisa membawa konsekuensi macam-macam.
Saya jadi ingat diri saya sendiri. Dulu kala, saya sering menulis kritik kepada Muhammadiyah dan kepada perilaku segenap warga yang bernaung di bawahnya. Saya berani melakukan itu karena dua hal. Pertama, secara genetis dan kultural saya juga warga Muhammadiyah. Jadi, apa yang saya lakukan itu semacam autokritik. Tapi yang kedua, sepertinya saya bisa plong tanpa beban karena saya tidak cukup kenal para aktivis struktural Muhammadiyah.
Begitu tulisan kritik saya kepada Muhammadiyah sering ramai, belakangan saya malah jadi bergaul dekat dengan banyak pegiatnya. Walhasil, lingkaran Muhammadiyah-struktural jadi salah satu lingkaran daring paling dominan di sekeliling saya. Hasil lebih jauhnya, saya jadi tak berani lagi asal mangap mengkritik Muhammadiyah.
Lucu, kan? Memang lucu. Padahal belum tentu juga tulisan atau posting-an saya dibaca oleh teman-teman Muhammadiyah. Tapi setidaknya, dengan kesadaran-kognitif bahwa ada banyak orang Muhammadiyah yang ada di dalam filter bubble saya, muncul imajinasi-afektif (kalau boleh saya katakan begitu) yang mengontrol saya, bahkan ketika sebenarnya mereka tidak melakukan kontrol sama sekali, atau bahkan ketika sebenarnya mereka blas tidak peduli.
Bolehlah kemudian kita bawa-bawa nama Foucault di sini. Pilihan pertemanan digital kita, juga pilihan kita untuk menerima teman-teman tertentu, adalah keputusan untuk menciptakan penjara panopticon bagi diri kita sendiri. Kita menyerahkan diri untuk diawasi, tapi juga memasrahkan diri untuk merasa-diawasi bahkan ketika sebenarnya sedikit pun kita tidak sedang diawasi.
Ketika sampai di pemahaman ini, ingin saya kembali mengintip unggahan Facebook Uda Brewok. Jangan-jangan sekarang dia posting foto sedang mengaji kitab kuning, atau duduk wirid sambil menggenggam untaian tasbih besar-besar. Kalau benar begitu, ingin saya iseng menaruh komen di wall-nya, “Udaaa, kutangnya manaaa?”
Tapi kemudian saya urungkan niat licik saya. Sebab mendadak saya ingat bahwa saya berteman dengan akun adik saya, dan akun adik saya itu dipegang emak saya. Dan saya pikir-pikir, ngoceh tentang kutang sambil diawasi emak saya itu rasanya kok ya, aduh, agak-agak gimana.
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)