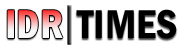Bangsa Penggemar Kerumunan

Jakarta –
Kalau ditanya apa yang paling berat dari segala tetek-bengek protokol kesehatan pencegahan Covid, saya akan menjawabnya dengan yakin: jaga jarak alias physical distancing. Inilah juga yang saya amati di mana-mana. Orang kadang masih tahan memakai masker, apalagi sekadar memencet botol kecil sanitizer. Tapi untuk berjalan sendiri-sendiri, duduk berjauh-jauhan, itu sulit sekali. Kita ini bangsa penggemar kerumunan. Dari upaya menegaskan eksistensi diri hingga meraih aktualisasi ya tak lepas dari urusan kerumunan.
Yang terjadi di Bandara Soetta dan Petamburan kemarin hanya salah satu contohnya. Seorang tokoh seagung Pak Rizieq, dengan sepak terjang yang heroik (minimal di mata para pengikutnya), yang sudah bertahun-tahun pergi jauh, lalu kembali dengan membawa harapan besar (sekali lagi: minimal di mata para pengikutnya), mustahil tidak menciptakan kerumunan. Dia pulang dengan semangat menantang. Tantangan yang dilambari penegasan bahwa dirinya masih perkasa itu mau tak mau mesti ditampilkan dengan pertunjukan kekuatan. Dan, pertunjukan kekuatan macam apa lagi yang bisa digelar selain pertunjukan massa? Bukankah pengakuan posisi publiknya pun hasil dari rentetan pameran kekuatan massa?
Saya sulit membayangkan Pak Rizieq berorasi lantang sekali, membakar ghiroh umatnya, tapi di hadapannya hanya ada sebiji dua biji kamera. “Ayo terus lawan kezaliman! Takbiiir!” sedangkan matanya hanya menatap kotak-kotak peserta forum Zoom yang diam dan beku, dengan fitur suara dimatikan dan tidak memunculkan gemuruh ribuan orang yang kompak berseru.
Tapi Pak Rizieq tidak sendiri. Ada berapa kabar yang Anda dengar selama pandemi ini tentang pelanggaran protokol di hajatan-hajatan pernikahan, selain pernikahan anak Pak Rizieq? Yang di video-video viral bolehlah kita pakai sebagai contoh. Tapi yang tidak tersebar lewat video? Saya kok yakin, jauh lebih banyak daripada yang kita duga. Bahkan saya sendiri sempat menghadiri salah satunya. Meski sejak awal diumumkan bahwa tamu di pesta yang saya datangi itu maksimal 50 orang, toh yang datang kemudian jadi 100, tambah lagi jadi 200, dan eh akhirnya jadi 500.
Angka 500 orang itu bisa jadi sudah angka paling kompromis bagi sebuah hajatan. Bukan semata karena empunya hajat kepingin rumahnya ramai. Tapi ini sudah perkara martabat, kehormatan, dan eksistensi. Ewuh mantu, alias hajatan menikahkan anak bagi banyak orang adalah semacam proklamasi puncak kesuksesan. Semakin megah ia, semakin banyak hadirinnya, semakin hebat-hebat orang-orang yang jadi tamu undangannya, akan menjadi pancang besar yang meneguhkan kejayaan si empunya hajat alias orangtua dari si pengantin. Mulai kejayaan karier, kejayaan pergaulan, kejayaan ekonomi, hingga kejayaan pengaruh sosial. Kondangan virtual? Aduh, apa itu kondangan virtual?
Maka, salah satu aturan yang benar secara medis tapi menggelikan secara psikologis adalah regulasi yang membatasi 100 orang saja untuk rapat umum alias kampanye Pilkada. Kampanye Pilkada adalah ajang show of force, nyaris tak beda dengan apa yang sudah dijalankan Pak Rizieq. Tak usahlah kita pura-pura lugu dengan membayangkan para calon pemilih dari kalangan massa buih bisa dirangkul dengan program-program yang inovatif, atau visi-misi yang solutif. Ya memang ada sih yang memakai jalur itu. Tapi berapa gelintir?
Selebihnya, cara paling efektif untuk menggaet pencoblos hanya ada dua, yaitu uang dan unjuk kekuatan massa. Maka, boro-boro 100 orang saat rapat “akbar” kampanye Pilkada, lha wong nyatanya pendaftaran Mas Gibran di KPU Solo saja sudah menciptakan kerumunan seribu manusia.
Dan, bukankah itu semua tidak berangkat dari ruang hampa? Periksa saja retorika-retorika pembakar nasionalisme yang sejak dulu kita simak bersama guru pelajaran sejarah dan Pancasila. Selain tentang jasa para pahlawan, yang selalu diteriakkan adalah betapa bangsa ini adalah bangsa yang besar. Dari sisi mana kebesarannya? Wibawanya di kancah dunia? Prestasi manusia-manusianya? Rasanya kok bukan. Kita besar karena populasi rakyatnya yang ratusan juta! Itulah kebanggaan kita, dan pelan-pelan membentuk konsep ideal keagungan yang selalu kita tata dalam segenap racikan cita-cita.
Kita sangat mengagungkan jumlah, Sodara. Kuantitas. Kita adalah bangsa yang telanjur membentuk identitas dan kebanggaan dengan berlandaskan pada kuantitas. Dengan kuantitas itulah kita membentuk kepercayaan diri kita, sambil melupakan fakta bahwa perubahan-perubahan besar di dunia lebih sering tidak tergantung kepada kekuatan jumlah.
Coba ingat, apakah dulu guru di sekolah Anda menekankan tentang kalahnya belasan ribu prajurit Mataram di tangan beberapa ratus serdadu Belanda pada 1629 di Batavia? Bukankah kita waktu itu lebih suka menyimak kisah kepahlawanan Sultan Agung saja? Seberapa banyak pula siswa sekolah yang mengerti bahwa Israel yang kecil itu dikeroyok tiga negara pada 1967, tapi menang dengan gemilang, membabat habis 20 ribu prajurit lawannya dan kehilangan kurang dari seribu saja tentaranya?
Kita sudah kadung jadi bangsa kerumunan, dan sangat menggemari kerumunan. Karena itulah, mau zaman berganti sekalipun, mau ruang-ruang digeser ke medium virtual sekalipun, kita tak bisa beranjak pergi dari kerumunan. Jadi jangan heran pula kalau medsos amat berjaya di udara negeri kita ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu rutin menempati posisi lima besar negara dengan konsumsi medsos paling rakus sedunia. Untuk apa? Boleh saja kita melihat sindrom narsisme dan sejenisnya, tapi lihat betapa kerumunan-kerumunan baru tercipta pula di sana.
Maka, setiap isu menciptakan kerumunan, setiap gesekan dan benturan membentuk kerumunan, bahkan setiap gosip receh pun memunculkan kerumunan. Di saat yang sama, kita mengeluh tentang fenomena para buzzer, para influencer, atau pasukan-pasukan siber. Sembari mengeluh, kita lupa bahwa mereka yang dibenci itu tak mungkin lahir jika kita sendiri tidak suka berkerumun, lalu menciptakan “pasar” sebagai buah dari keramaian demi keramaian.
Kita mungkin membenci wabah dan kematian, sebab mencintai kesehatan dan kehidupan. Tapi dari apa yang terus terjadi dan tak henti menyajikan bukti-bukti, agaknya diam-diam sebenarnya kita lebih cinta kepada gairah di dalam kerumunan-kerumunan.
Iqbal Aji Daryono penulis, tinggal di Bantul
(mmu/mmu)